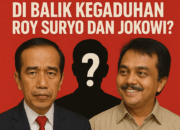Masalahnya Bukan Sekadar Ijazah
Perdebatan tentang “ijazah palsu” Joko Widodo kelihatannya soal dokumen pendidikan, tetapi yang sebenarnya dipertaruhkan jauh lebih besar:
legitimasi moral dan kepercayaan publik terhadap pemimpin, pemilu, dan negara.
Tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu sudah berulang kali muncul di ruang publik, terutama di masa polarisasi keras pasca-Pilpres 2014 dan 2019. Sejumlah pihak bahkan menempuh jalur hukum untuk menggugat keabsahan ijazah tersebut.
Namun sampai batas pengetahuan saya (hingga 2024):
- Pengadilan telah menolak gugatan yang menuduh ijazah Jokowi palsu (antara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat).
- Pihak sekolah dan universitas yang dikaitkan dengan Jokowi telah menyatakan bahwa dokumen ijazahnya asli dan sesuai arsip mereka.
- Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan “ijazah Jokowi terbukti palsu”.
Artinya, secara hukum formal dan dokumen resmi, tuduhan “ijazah palsu” sampai hari ini belum terbukti. Namun menariknya, narasi itu tetap hidup, disebarkan, diperdebatkan, dan dipercaya oleh sebagian orang.
Di sinilah kita perlu bertanya: Mengapa sebuah tuduhan yang tidak terbukti secara hukum bisa bertahan begitu lama dan keras di benak publik?
Jawabannya membawa kita pada dua hal:
- cara kerja disinformasi dan buzzer berbayar,
- akumulasi kekecewaan atas janji-janji politik yang dianggap bohong.
Mengapa Narasi Ijazah Palsu Begitu “Laku”?
Isu pendidikan seorang pemimpin biasanya sensitif karena menyentuh integritas pribadi dan kelayakan memimpin. Di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, skandal ijazah (nyata maupun tuduhan) sering dipakai sebagai senjata politik.
Dalam konteks Jokowi, ada beberapa faktor yang membuat isu ini “laku jual”:
1. Polarisasi yang ekstrem sejak 2014
Sejak Pilpres 2014, politik Indonesia terbelah tajam. Di satu sisi ada pendukung fanatik yang mengagungkan Jokowi, di sisi lain ada kelompok yang sejak awal menganggapnya tidak layak, bahkan melihatnya sebagai simbol “pengkhianatan” elit pada rakyat.
Dalam polarisasi seperti ini, segala tuduhan negatif mudah sekali dipercaya oleh kubu yang sudah tidak suka.
2. Ketidakpercayaan pada institusi
Ketika lembaga negara, aparat hukum, dan kampus menyatakan ijazah Jokowi asli, sebagian warga yang sudah tidak percaya pada negara akan menjawab: “Pasti sudah diskenariokan.”
Jadi apa pun klarifikasinya, bagi kelompok ini, fakta formal tidak lagi dipercaya. Yang dipercaya adalah narasi yang memperkuat rasa marah dan kecewa mereka.
3. Akumulasi kekecewaan atas janji politik
Di mata para pengkritik, Jokowi dianggap banyak “berbohong” atau paling tidak tak konsisten antara janji dan kebijakan.
Ketika seorang pemimpin dianggap sering tidak jujur dalam kebijakan, publik yang kecewa akan lebih mudah percaya pada tuduhan ekstrem—termasuk yang tidak terbukti, seperti “ijazah palsu”.
4. Ekosistem media sosial yang mempercepat hoaks
Platform digital memberi ruang luas bagi narasi yang:
- sensasional,
- memancing emosi,
- mengkonfirmasi prasangka yang sudah ada.
Tuduhan ijazah palsu memenuhi semua kriteria itu: dramatis, pribadi, dan cocok untuk mengguncang legitimasi.
Dengan kata lain, isu ijazah bukan hanya soal dokumen. Itu adalah gejala dari krisis kepercayaan yang lebih dalam.
Peran Buzzer Berbayar: Mengubah Fakta Jadi Perang Persepsi
Istilah “buzzer bayaran” atau “buzzer RP” kini sudah menjadi kosa kata politik sehari-hari di Indonesia. Sejumlah riset dan laporan media menyebut adanya:
- jaringan akun pro-pemerintah yang secara konsisten membela kebijakan, menyerang pengkritik, dan mengarahkan percakapan di media sosial,
- jaringan akun oposisi yang secara sistematis menyerang pemerintah, menyebarkan narasi delegitimasi, termasuk terkait ijazah, agama, dan asal-usul Jokowi.
Beberapa pola yang sering terlihat:
1. Serangan terhadap pengkritik isu ijazah
Ketika ada pihak yang menggugat atau mempertanyakan ijazah Jokowi, segera muncul:
- serangan personal (doxing, label “kadrun”, “radikal”, dll.),
- framing bahwa pengkritik adalah penyebar hoaks yang harus dibungkam.
Di sisi lain, ada juga jaringan yang mengangkat isu ijazah ini berulang-ulang untuk menggiring persepsi bahwa Jokowi adalah pemimpin ilegal, apa pun fakta hukumnya.
2. Produksi “kebenaran alternatif”
Buzzer tidak hanya menyebarkan link berita; mereka menciptakan narasi, mengulang, mengolah, mengemas ulang, hingga sebuah klaim tampak seperti “kebenaran umum”.
Dalam konteks ijazah:
- kubu pro akan terus menekankan: “ini sudah hoaks, selesai,”
- kubu anti akan terus menekankan: “negara menutupi kejahatan besar.”
Yang hilang: diskusi rasional berbasis bukti.
3. Normalisasi fitnah sebagai strategi politik
Ketika angka keterlibatan buzzer tinggi, batas antara kritik sah, fitnah, dan kampanye hitam menjadi kabur. Tuduhan serumit “ijazah palsu” bisa diperlakukan sama entengnya seperti meme ejekan.
Implikasinya:
- reputasi pribadi bisa hancur tanpa dasar kuat,
- publik makin bingung membedakan mana fakta, mana propaganda.
Dalam suasana seperti ini, bahkan klarifikasi resmi dari kampus atau putusan pengadilan pun bisa kalah kuat dibanding ribuan cuitan yang diorkestrasi.
Janji Politik, “Kebohongan”, dan Latar Kekecewaan
Untuk memahami mengapa sebagian warga begitu mudah memegang teguh isu “ijazah palsu”, kita perlu melihat konteks dua periode pemilu Jokowi (2014 dan 2019) dan persepsi soal janji politik.
Banyak pengkritik menuduh Jokowi “berbohong”, misalnya dalam hal:
1. Janji tidak bagi-bagi kursi kepada partaiKekecewaan
- Dalam kampanye, Jokowi pernah menekankan perlunya kabinet profesional.
- Dalam praktik, komposisi kabinet diisi banyak kader partai dan kompromi politik.
- Bagi pengkritik, ini bukti janji tak ditepati.
2. Sikap terhadap KPK dan pemberantasan korupsi
- Di awal, Jokowi dipersepsikan sebagai figur antikorupsi.
- Kemudian muncul revisi UU KPK (yang banyak dinilai melemahkan), serta penunjukan sejumlah pejabat kontroversial.
- Kubu kecewa menyimpulkan: ada jarak lebar antara retorika dan kebijakan.
3. Janji perlindungan warga dari kriminalisasi dan pembatasan kebebasan berekspresi
- Di lapangan, banyak aktivis, jurnalis, dan warga biasa terkena jerat UU ITE dan pasal-pasal karet lainnya.
- Ini menumbuhkan perasaan bahwa kritik dibungkam, bukan dirangkul.
4. Omnibus Law dan isu ketenagakerjaan
- Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
- Omnibus Law Cipta Kerja dipandang banyak buruh dan akademisi sebagai merugikan pekerja dan terlalu berpihak pada investor.
- Di sini, janji “pro-rakyat” dinilai berbalik menjadi “pro-oligarki”.
Daftar ini bisa diperpanjang, tetapi pola utamanya jelas:
Ada gap besar antara ekspektasi (dibentuk oleh kampanye dan citra awal Jokowi) dengan kenyataan kebijakan.
Bagi sebagian orang, gap ini dibaca sebagai:
- bukan sekadar kompromi politik yang tak terhindarkan,
- melainkan “kebohongan sistematis” demi meraih dan mempertahankan kekuasaan.
Begitu label “pembohong” tertanam kuat, maka:
- setiap kebijakan merugikan akan dianggap konfirmasi,
- setiap tuduhan miring—bahkan yang belum terbukti, seperti “ijazah palsu”—akan terasa masuk akal.
Di sinilah kaitan kuat antara:
- tuduhan ijazah palsu,
- jaringan buzzer yang mengulang dan menguatkan narasi,
- kekecewaan mendalam pada dua periode kekuasaan.
Ketika Fakta Kalah dari Narasi
Kita bisa menyimpulkan beberapa hal:
1. Soal ijazah Jokowi, secara hukum dan dokumen resmi sampai saat ini tidak terbukti palsu.
Tuduhan-tuduhan di pengadilan tidak dikabulkan, dan lembaga pendidikan yang bersangkutan mengonfirmasi keaslian.
2. Namun di ranah opini publik, banyak orang tidak lagi peduli pada status hukum.
Mereka menilai berdasarkan:
- rasa percaya atau tidak percaya,
- pengalaman subjektif,
- narasi yang terus-menerus mereka konsumsi di media sosial.
3. Buzzer berbayar dan jaringan propaganda digital (baik pro maupun anti pemerintah) memperparah situasi dengan:
- mengubah isu menjadi senjata politik,
- menaikkan volume hoaks dan setengah-fakta,
- melemahkan batas antara kritik sah dan fitnah.
4. Kebohongan atau inkonsistensi dalam janji politik—atau setidaknya yang dipersepsikan demikian—mendorong publik untuk semakin sinis.
Sinisme ini menjadi tanah subur bagi segala macam tuduhan ekstrem, termasuk yang tidak pernah terbukti.
Apa Pelajaran yang Bisa Diambil?
Dari kontroversi ini, beberapa pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia:
1. Verifikasi fakta tetap wajib, meski kita kecewa pada rezim mana pun
Tidak suka pada seorang politisi bukan alasan untuk menerima semua tuduhan tanpa bukti.
Jika kita melawan kebohongan dengan kebohongan lain, kita justru:
- menghancurkan standar kebenaran,
- memudahkan penguasa otoriter mana pun (di masa depan) untuk berkata: “Semua ini cuma perang hoaks kok.”
2. Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik harus diperkuat
- Dokumen dan rekam jejak pejabat penting seharusnya mudah diaudit dan diakses, bukan sekadar diumumkan satu kali lalu selesai.
- Jika sejak awal transparan dan sistematis, ruang bagi teori konspirasi akan menyempit.
3. Regulasi dan etika kampanye digital perlu dibangun serius
- Pendanaan buzzer politik yang masif dan tersembunyi adalah ancaman langsung bagi demokrasi.
- Partai dan kandidat seharusnya didorong (atau diwajibkan) melaporkan strategi dan pengeluaran kampanye digital secara terbuka.
4. Warga perlu membangun daya tahan terhadap manipulasi
- Literasi media bukan sekadar soal cek fakta, tapi juga memahami bagaimana emosi dan kemarahan kita dipakai sebagai bahan bakar algoritma.
- Kita perlu berlatih menahan diri: tidak langsung membagikan tuduhan personal tanpa dasar kuat, meski itu sejalan dengan preferensi politik kita.
Di Antara Harapan dan Kekecewaan
Dua periode kepemimpinan Jokowi meninggalkan jejak kompleks:
ada pembangunan infrastruktur masif, ada juga kekecewaan mendalam terhadap kualitas demokrasi, penegakan hukum, dan keberpihakan pada kelompok lemah.
Isu ijazah palsu, buzzer berbayar, dan tuduhan kebohongan dalam pemilu adalah bagian dari cerita besar tentang krisis kepercayaan itu.
Di satu sisi, wajar jika publik marah dan kritis.
Di sisi lain, jika kemarahan itu membuat kita:
- mudah memeluk tuduhan yang belum terbukti,
- nyaman dengan fitnah karena terasa “sejalan dengan perasaan”,
maka pada akhirnya yang kalah bukan hanya satu tokoh atau satu rezim, tetapi kualitas nalar publik kita sendiri.
Demokrasi yang sehat bukan hanya butuh pemimpin yang jujur,
tetapi juga warga yang kritis sekaligus adil: keras terhadap kebohongan, namun juga hati-hati terhadap fitnah—termasuk ketika fitnah itu menguntungkan posisi politik kita.